Mempertanyakan Yang Lewat di Depan mata
Judul Buku: Pahlawan & Tikus
Penulis:
A. Mustofa Bisri
Jumlah
halaman: 120 halaman
Penerbit:
Diva Press
Tanggal-bulan-tahun
diterbitkan: 1995, terbit ulang Diva Press 2019
Sebagai seorang
penulis puisi ala-ala, selama ini aku masih terpaku dengan buku-bukunya Aan
Mansyur sehingga suka ikut-ikutan sendu. Dalam beberapa kesempatan, pingin
banget rasanya untuk keluar dari Aan dan mencicipi puisi dari penulis lain,
mencontek gayanya, lalu mengembangkannya jadi puisi sendiri.
Sampai dalam
suatu kesempatan yang kebetulan, aku melihat cuplikan ucapan K.H. Mustofa Bisri
(Gus Mus) dalam sesinya di Mata Najwa
“Wah, lihat itu dia (Sujiwo Tejo). Orangnya ngga punya apa-apa, tapi juga
ngga butuh apa-apa. Kaya banget itu dia.”
Ucapan itu
dilontarkan ketika sesinya Gus Mus membahas tentang mengapa koruptor itu tidak
puas-puas korupsi padahal mereka sudah banyak yang kaya? Mendengar hal ini, aku
pun tertarik dengan pribadi Gus Mus yang merupakan seorang ulama, dan juga
seorang penulis puisi. Oleh sebab itu, ketemulah aku dengan salah satu bukunya,
“Pahlawan dan Tikus”
Berbagai puisi
dalam kumpulan Pahlwan dan Tikus dibagi menjadi enam bab. Ada Puisi Gelap,
Remang-Remang, Agak Terang, Terang, Terang-Terangan, sampai penerang. Semula gw
kira penamaan bab ini dilandaskan pada emosi yang ingin disampaikan oleh
penulis, yaitu emosi “gelap” atau emosi “terang”. Atau kalau merujuk kepada
Sapardi Djoko Damono, ada juga puisi yang disebut sebagai “Puisi Terang”, yaitu
puisi yang lurus langsung menyampaikan maknanya tanpa perlu interpretasi yang
macam-macam.
Namun, setelah
dibaca, perasaan yang timbul ketika bersalaman dengan tiap babnya malah
cenderung sama, yakni “Gelap” semua. Perasaan ini timbul sebab mayoritas puisi
ini ditujukkan kepada elite penguasa yang dianggap lalai dalam mengurus negara,
setidaknya pada tahun puisi tersebut dituliskan. Meskipun ada beberapa puisi
selingan bertema cinta atau keluarga, isu utama yang diangkat oleh Gus Mus
lebih banyak menyoal politik atau kenegaraan. Bahkan, puisi yang dikategorikan
sebagai “Puisi Gelap”, sejatinya tidak gelap-gelap amat sebab kata dan diksi
yang digunakan cukup mudah dipahami sekali baca.
Kritik dan
masalah-masalah sosial yang diangkat juga disampaikan dengan bahasa yang
sederhana, dengan perumpanaan yang sudah lazim dan gw yakin orang Indonesia
pasti bisa mengira-ngira “siapa” dan “apa” yang ditunjuk-tunjuk Gus Mus dalam
puisinya. Barangkali, keresahan yang dialami Gus Mus dalam melihat berbagai
problematika di negeri ini juga sebetulnya dialami oleh pembaca sehingga timbul
semacam hubungan tak kasat mata lantaran ada kesamaan keresahan antara penulis
dan pembaca. Puisi Gus Mus mampu memunculkan emosi yang sekian lama mengendap
di benak orang Indonesia. Lihat saja puisi pertama di buku ini yang berjudul
“Pahlawan” berikut ini:
Lahir. Hilang. Gugur. Hidup.
Mengalir. Sudah
Lewat
baris-baris puisi sederhana di atas, Gus Mus sukses membuat pembaca
mempertanyakan mengenai makna dari hal-hal yang sering kali luput di benak
orang-orang Indonesia. Sebagai orang yang juga turut aktif membaca berita dalam
negeri, emosi yang gw rasakan malah cenderung “Gelap”, atau cenderung sedih dan
marah. Di balik keindahannya, Indonesia, negeri ini menyimpan berbagai
teka-teki yang bisa membuat kita bertanya-tanya, “kok gini amat, ya?” Kekuatan
puisi ini justru terletak pada kesederhanaannya. Gus Mus mahir sekali memainkan
dan menerangkan perkara-perkara negara ke dalam bahasa awam, sehingga dapat
mengena setidaknya bagiku sendiri. Konflik dalam puisi ini semakin naik,
apalagi ketika bab berganti ke “Puisi Terang-Terangan” yang mengangkat berbagai
tragedi yang terjadi di dunia nyata seperti penggusuran wilayah, marsinah, atau
pembantaian Karbala.
ada berita pe-ti-ga berlaga
ada berita pe-de-I
berkelahi
ada berita golkar
bertengkar
ada berita abri tahu
sendiri
ketika itu dimanakah
sebenarnya posisi kita,
bangsa Indonesia?
Poinnya adalah,
di dalam kumpulan ini puisi-puisinya disusun dengan satu tema utama: kejujuran
atas apa yang terjadi dan dirasakan oleh penulis terhadap negeri. Makanya, pada
lima bab semula pembaca diajak untuk memikirkan kembali, atau menengok
kenyataan yang barangkali sengaja kita alihkan muka daripadanya. Lima bab ini
memiliki tema yang sama, serta pendirian yang teguh tidak berubah sehingga
puisi-puisinya dapat menyampaikan emosi yang kuat kepada pembaca.
Akan tetapi,
meskipun emosi yang disampaikan dalam berbagai puisinya sangat kuat terasa,
selain kritik sosial Gus Mus juga piawai menyelipkan puisi-puisi lain bertema
cinta atau keluarga di tengah hiruk pikuknya mengkritisi negara. Tengok saja
kutipan puisi berjudul “Kaukah Sepi Itu?” berikut ini
Aku tak pernah berkata kepada
sepi
jangan menggangguku
sepi tak pernah berkata
kepadaku
aku ingin menungguimu
tapi aku dan sepi terus
saling terpaku
kaukah sepi itu?
Puisi-puisi ini
mampu membuat gw senyum-senyum sendiri, sekaligus menjadi tempat untuk mengisi
tenaga sebelum kembali berhadapan dengan realita pahit para penguasa.
Namun, dengan
segala kritik dan emosi yang coba disampaikan lewat buku puisi ini, yang paling
menarik bagi gw adalah bagaimana penulis memutuskan untuk mengakhiri buku
puisinya. Dalam bab akhir, “Puisi Penerang”, tiga buah puisi yang ditulis di
bab ini semakin menegaskan latar belakang Gus Mus yang merupakan seorang pemuka
agama. Meskipun dalam kenyataannya, di negeri ini tentu seorang ahli agama
sering ditanya tentang perihal segala apa, namun Gus Mus memilih untuk
merendahkan hati dan mengajak pembacanya berdoa, yang kembali mengingatkan kita
bahwa segala-galanya, pada akhirnya, akan kembali ke tangan Yang Maha Kuasa.
Ya Allah, Wahai Tuhanku;
kebaikan apa pun yang
Engkau anugerahkan kepadaku dan
aku tak memujiMu tanpa
kusadari atau kusadari
aku bertobat darinya dan
berserah diri
seraya mengucap Laa
ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah
shallallahu ‘alaihi
wasallam
Ending yang
tidak menggurui, mengingatkan kita semua untuk kembali mendasarkan sesuatu
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Salah satu buku
penting yang mengawal jalannya demokrasi di negeri ini. Selain ditulis dengan
bahasa yang mudah dipahami awam, buku ini sama-sama mengajak pembacanya untuk
senantiasa berpikir, mencoba memahami realita politik yang terjadi belakangan
ini, serta agar kita senantiasa tunduk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Perjalanan
yang menarik, menyusun lembah kegelapan di “Puisi-Puisi Gelap” milik Gus Mus
sampai tercerahkan di “Puisi-Puisi Penerang”nya. Meskipun beberapa puisi
umurnya telah mencapai lebih dari 20 tahun, entah kenapa kritik dan kondisi
yang dilukiskan di dalamnya masih berbunyi nyaring sampai sekarang. Entah
kenapa.

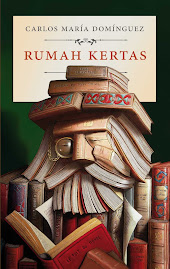
Komentar
Posting Komentar